Nabire — Di Warkop Kedai Titik Nol, Bumi Wonorejo, Nabire, sore itu kopi bukan satu-satunya yang menghangat. Buku-buku terbuka, gagasan berkelindan, dan suara-suara muda Papua saling menyapa dalam kegiatan Lapak Baca dan Diskusi Lingkar Studi Papua (LSP), Rabu (4/1/2026). Ruang sederhana itu kembali menjadi tempat belajar bersama—di mana literasi dipraktikkan sebagai kesadaran sosial dan bentuk perlawanan terhadap berbagai penindasan yang dialami rakyat Papua.
Sejumlah pemuda dan aktivis terlibat aktif dalam diskusi, membedah persoalan rakyat dengan bahasa yang jujur, membumi, dan kritis. Diskusi berlangsung cair, namun tajam, menempatkan membaca dan berdialog sebagai fondasi perjuangan sosial.
Koordinator LSP, Boas Bayage, menegaskan bahwa pendidikan sejati harus berpihak pada rakyat.
“Bila kaum muda terpelajar merasa dirinya terlalu tinggi untuk berbaur dengan masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Menurut Boas, dalam situasi kolonialisme yang menindas, membaca, berdiskusi, dan beraksi adalah senjata utama rakyat. Kolonialisme, katanya, tidak pernah mengajarkan perlawanan—melainkan kepatuhan. Karena itu, literasi menjadi jalan untuk membongkar watak penindasan yang dilembagakan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Abbi Douw, yang menilai perubahan sosial tidak mungkin lahir tanpa pemahaman yang utuh. Literasi, baginya, menjadi jembatan untuk menautkan masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui proses membaca, menganalisis, berdiskusi, serta menguji gagasan di tengah realitas masyarakat.
Sementara itu, Abeth menekankan pentingnya budaya membaca sebagai fondasi pemulihan sosial dan budaya Papua. Tanpa budaya tersebut, kehancuran sosial hanya tinggal menunggu waktu.
Dimensi ideologis diskusi mengemuka ketika Nato memandang literasi sebagai dasar materialisme ilmiah untuk membangun masyarakat yang adil dan berbudaya—sebagai alternatif atas dominasi kapitalisme dan imperialisme global. Diskusi semakin tajam saat Soni menyoroti bagaimana ilmu pengetahuan kerap dikunci demi akumulasi modal.
“Dengan membaca, kita memenggal narasi musuh dan membangun manuver menuju masyarakat baru,” tegasnya.
Bagi Yikai M, literasi adalah “nyawa” yang membuat manusia peka terhadap realitas sosial. Tanpanya, manusia seperti kehilangan napas. Senada, Eko-Vincent menilai membaca dan berdiskusi sebagai senjata berpikir kritis dalam menghadapi tiga ancaman utama rakyat Papua: kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme.
Di sisi lain, Anton mengingatkan bahwa literasi pun dapat dikendalikan penguasa untuk kepentingan eksploitasi tenaga kerja. Karena itu, analisis kritis menjadi syarat mutlak agar literasi benar-benar membebaskan rakyat dari isolasi dan penghisapan.
Isu gender turut mendapat perhatian serius. Lin menegaskan bahwa di tengah bekerjanya kapitalisme, kolonialisme, militerisme, dan patriarki secara bersamaan, lapak baca hadir sebagai ruang perlawanan alternatif.
“LSP bukan sekadar ruang baca, tetapi praktik politik untuk merebut kembali pengetahuan dari logika kekuasaan,” ujarnya.
Melalui lapak baca, kesadaran kelas dan gender dibangun secara kolektif—menolak tunduk dan menolak takut. Lingkar Studi Papua pun diharapkan terus menjadi ruang aman bagi kaum muda Papua untuk membaca, berdiskusi, dan membangun kesadaran kritis demi masa depan Tanah Papua.


















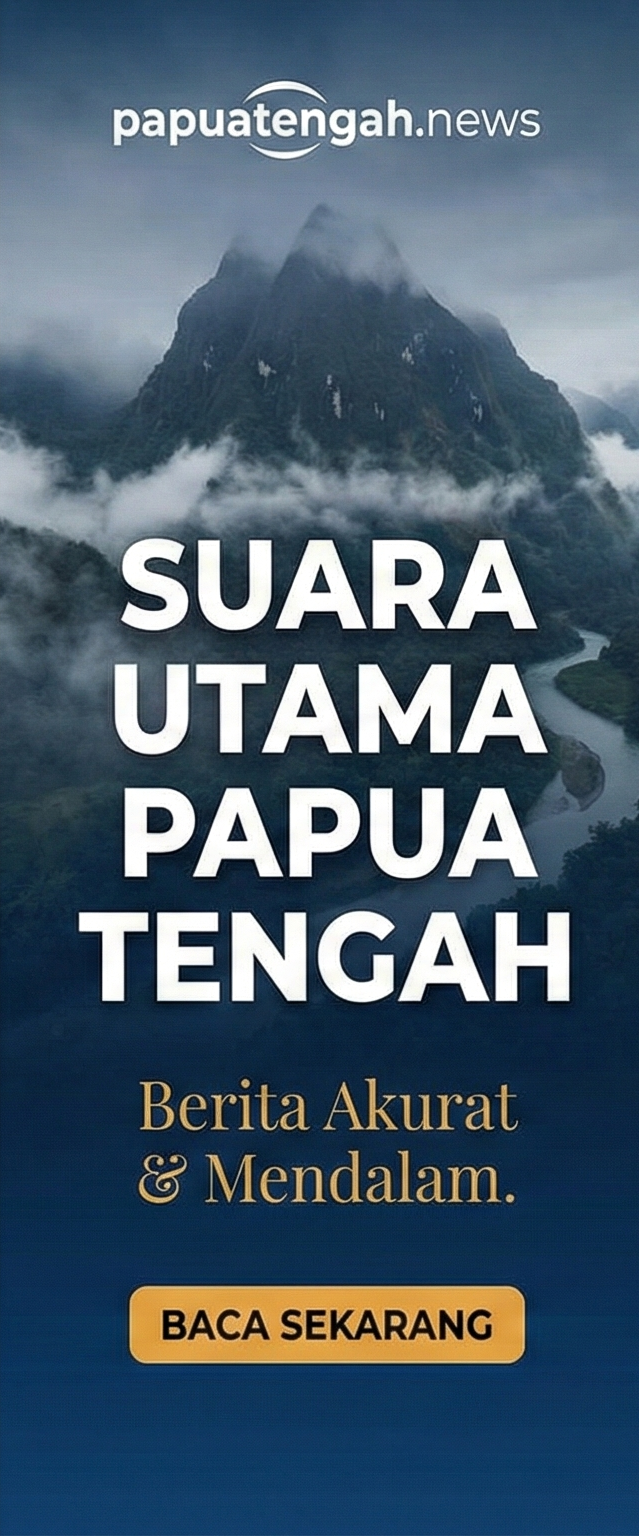
Komentar